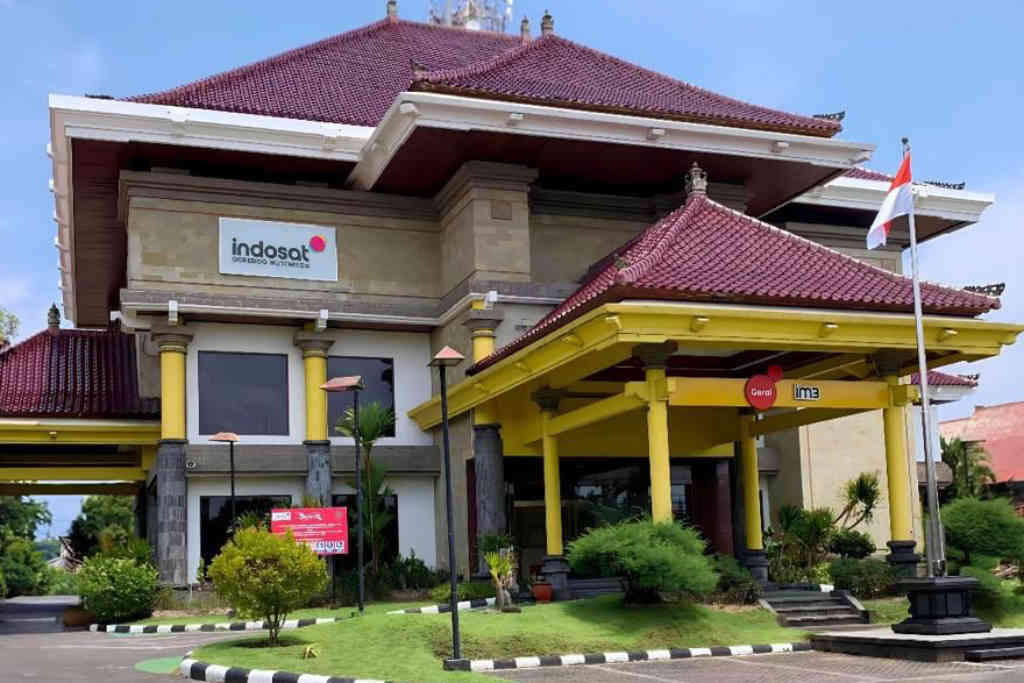Memaknai Hari Suci Nyepi di Era Antroposen

Oleh Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si
Alam raya (buana agung) ini dimaknai sebagai hal yang melingkupi kehidupan manusia dan tidak dapat diatur atau dipahami sepenuhnya (misteri).
Sedangkan antroposen adalah era geologis di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan utama yang
memengaruhi perubahan ekosistem bumi. Istilah ini menandai pergeseran dari era Holosen, ketika perubahan alam lebih dipengaruhi oleh faktor alamiah, ke era di mana
manusia menjadi penggerak utama krisis lingkungan.
Era antroposen memiliki ciri-ciri antara lain, pertama krisis iklim. Hal ini ditandai dengan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas industri dan transportasi.
Kedua, deforestasi yakni penggundulan hutan untuk pertanian, pertambangan, dan urbanisasi.
Ketiga, polusi berupa limbah plastik, polusi udara dan pencemaran air yang merusak ekosistem.
Keempat, kehilangan keanekaragaman hayati, di antaranya kepunahan massal spesies akibat perburuan, perusakan habitat, dan perubahan iklim.
Manusia era antroposen juga memiliki ciri berupa gaya hidup konsumtif dan eksploitasi berlebihan yang mempercepat krisis ekologi. Manusia dalam antroposen sering memandang alam sebagai objek untuk dieksploitasi, bukan entitas yang harus dihormati.
Antroposen tidak hanya krisis ekologis, tetapi juga spiritual.
Keterputusan manusia dari alam memicu kekosongan batin dan ketidakseimbangan kosmik.
Dalam konteks Hindu, ini melanggar prinsip rta (tatanan kosmis) dan dharma (kebenaran universal).
Konsep antroposen mempertegas urgensi ajaran Hindu seperti Tri
Hita Karana—harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam.
Konsep ini juga mengingatkan kembali pada prinsip moderasi, jalan tengah untuk menghindari eksploitasi ekstrem maupun pengabaian terhadap lingkungan.
Relevansi
Lalu bagaimana relevansi antroposen dengan perayaan Hari Raya Nyepi –sepi, kosong, hening, senyap?
Hari suci Nyepi sebagai praktik spiritual bagi umat Hindu, memberikan
ruang untuk refleksi diri, merenungkan bagaimana manusia berkontribusi pada kerusakan atau
pemulihan bumi.
Hari suci Nyepi menjadi momen ekologis di mana aktivitas manusia berhenti sejenak, membiarkan bumi
bernapas, relevan dengan semangat melawan krisis antroposen.
Konsep dasar Nyepi adalah Catur Brata Penyepian yakni Amati Geni. Makna fisiknya berupa larangan menyalakan api atau penerangan. Makna filosofisnya berupa simbol pengendalian hawa nafsu (kama) dan ego, mengajak manusia merenung dalam kegelapan agar menemukan cahaya batin.
Sedangkan relevansi antroposen yakni mengurangi konsumsi energi dan polusi cahaya. Ini selaras dengan gerakan hemat energi global.
Amati Karya, makna fisiknya tidak melakukan aktivitas fisik atau pekerjaan duniawi. Makna filosofisnya mengajarkan jeda untuk refleksi diri dan menekan keserakahan material (lobha), memperkuat kesadaran spiritual.
Relevansi antroposen, mengurangi produksi dan konsumsi berlebihan yang mempercepat eksploitasi sumber daya alam.
Amati Lelungan, makna fisiknya berupa larangan bepergian ke luar rumah atau desa.
Makna filosofisnya mengajarkan ketenangan batin dan introspeksi, simbol dari perjalanan ke dalam diri sendiri (antaratma yatra). Relevansi antroposen yakni mengurangi jejak karbon akibat transportasi, sejalan dengan prinsip mobilitas ramah
lingkungan.
Amati Lelanguan, makna fisiknya menghindari hiburan, musik, atau
kesenangan indrawi. Makna filosofisnya melatih pengendalian diri dan kesederhanaan, membebaskan diri dari ketergantungan duniawi.
Relevansi antroposen: Mengajarkan pola hidup sederhana dan mengurangi budaya konsumtif yang memperparah krisis ekologi.
Bagaimana reaktualisasi ajaran agama dalam konteks modern?
Agama bukan hanya warisan masa lalu, tetapi sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan kekinian. Nyepi,
misalnya, bisa dimaknai lebih luas sebagai momentum introspeksi ekologis dalam konteks krisis antroposen.
Sementara itu tradisi keagamaan mampu memperkuat solidaritas sosial, menginspirasi gerakan sosial, dan mempromosikan keadilan lingkungan melalui ajaran kasih sayang, gotong-royong, dan tanggung jawab kolektif.
Sementara itu prinsip moderasi membantu mencegah ekstremisme, baik dalam eksploitasi sumber daya
alam maupun pengabaian terhadap pembangunan.
Jalan tengah ini relevan dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Tradisi keagamaan, termasuk Hindu, menawarkan prinsip moral dan etika yang relevan untuk menghadapi
tantangan global seperti krisis iklim, ketidakadilan sosial,
dan konflik kemanusiaan.
Nilai-nilai lokal yang diwariskan melalui tradisi keagamaan sering kali memiliki prinsip universal, seperti keseimbangan alam (rta), yang sejalan dengan konsep keberlanjutan
global. Tradisi keagamaan mendorong keterhubungan manusia dengan alam. Dalam Hindu, konsep Tri Hita Karana mengajarkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan lingkungan, yang menjadi
solusi spiritual bagi kerusakan ekosistem.
Di era antroposen, generasi muda Hindu memiliki peran strategis sebagai penggerak utama gerakan sadar lingkungan. Memanfaatkan nilai-nilai spiritual Hindu seperti Tri Hita
Karana untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal Hindu, seperti penggunaan energi terbarukan, pertanian
organik berbasis subak, dan praktik konservasi alam.
Mengembangkan solusi kreatif untuk mengurangi jejak karbon, seperti eco-bricks, zero-waste lifestyle, dan
pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Generasi muda Hindu memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat melalui media sosial tentang relevansi ajaran Hindu dalam menjaga lingkungan. Kemudian dengan kemajuan informasi dan teknologi, generasi muda Hindu bisa menggelar kampanye digital tentang Nyepi ekologis sebagai refleksi nyata dari krisis antroposen. (*)
Penulis, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI